Bukan Tanah, Tapi Ruang.
Kemarin
ketika sedang berhenti di sebuah lampu merah, aku melihat ada satu mural
yang menarik. Mural ini ukurannya lumayan gede karena dibuat pada dinding
sebuah deretan toko yang tepat berada di salah satu sudut perempatan.
Sebenernya bukan gambarnya yang membuatku tertarik -fyi aku selalu suka
mengamati mural- melainkan tulisan yang dilukis tepat di tengah2nya dengan
ukuran yang lumayan nyolok mata.
Tulisan di
mural itu kurang lebih begini:
“Setiap
Orang Butuh Tanah”
Mural ini
ada sejak isu jogja ora didol (jogja
tidak dijual) menjadi tren akhir2 ini sebagai respon terhadap merebaknya
pembangunan hotel dan mall di Jogja.
Cuma kali
ini aku gak mau ngebahas soal permasalahan tren pembangunan bangunan komersil
di jogja, jadi anggap aja ini sekilas info karena ada yang lebih menarik untuk
ditulis.
Membaca
tulisan itu mengingatkanku pada salah satu permasalahan pembangunan khususnya
pembangunan perkotaan yang dulu sempat disinggung2 di salah satu kuliahku.
Lalu apakah
permasalahan itu?
Dari sebuah
kalimat, kita dapat menangkap persepsi orang yang bersangkutan. Begitu pula
melalui kalimat pada mural ini. ‘setiap orang butuh tanah’ merupakan sebuah kalimat
yang merefleksikan persepsi masyarakat, dan dalam hal ini persepsi yang tertangkap
adalah mengenai persepsi terhadap pentingnya tanah.
Orang Indonesia,
khususnya orang jogja kebanyakan masih menganggap bahwa tanah adalah kebutuhan
utama dalam hidup, mindset ini sudah
tertanam secara turun menurun dalam setiap keluarga yang ada di kota ini.
Ini nggak
akan jadi masalah jika yang ngomong adalah orang desa yang kebanyakan adalah
petani secara mereka memang butuh tanah untuk diolah. Namun, ini akan jadi
masalah jika dikatakan oleh orang yang hidup di perkotaan seperti di Jogja ini.
Tanah adalah
sebuah permasalahan klise di dalam perkembangan perkotaan dimana logika
dasarnya, Luasan tanah selalu tetap sementara jumlah orang diatasnya
selalu bertambah.
And then what?
Persepsi
masyarakat ini dianggap tidak fleksibel dengan perkembangan yang ada dan jika
tidak segera diubah, maka akan terjadi masalah yang lebih serius dari sekedar
masalah ‘tidak kebagian tanah’.
Untuk menyiasati
permasalahan keterbatasan lahan di perkotaan, beberapa negara di luar negeri
sudah menerapkan inovasi vertical
building, baik untuk tempat tinggal maupun tempat bekerja. Gedung2 pencakar
langit dibangun menjulang di tengah2 kota dan apartemen yang tidak kalah tinggi
berderet mengelilinginya. Dan ya..permasalahan keterbatasan lahan teratasi
dengan sesederhana itu.
Hanya saja
untuk beberapa kota di Indonesia seperti Jogja, solusi vertical building belum bisa dikatakan sebagai solusi yang simple,
misalnya kasus rusun di Jogja. Dulu saat awal2 pembangunan rusun, banyak sekali
kendala yang berasal dari masyarakat. Mulai dari keengganan untuk tinggal di
‘ketinggian’ dan tidak menjejak tanah, bayangan tentang ‘rumah tanpa halaman’
serta alasan teknis seperti kelelahan harus naik tangga. Berbagai kendala ini
menjadikan solusi vertical building bahkan tidak masuk kedalam deretan solusi.
Dari sini
dapat kita lihat bahwa persepsi masyarakat sangat menentukan arah perkembangan
sebuah kota. Dulu, aku selalu pusing jika diminta untuk memikirkan sebuah jalan
keluar untuk masalah yang sudah bawa2 cara pikir begini.
Namun setelah
sekian lama pertanyaan itu terlontar, akhirnya jawaban itu nyangkut di kepala.
Iya, setelah sekian lama akhirnya aku nemu jawabannya. Pas lagi panas2an di
lampu merah, pas ditengah2 kumpulan kendaraan berasap, pas lagi mantengin
sebuah dinding, aku nemu jawabannya, great!
Persepsi does change
Bahkan tanpa
perlu kita ubah, persepsi tetap akan berubah.
Karena apa?
Karena persepsi merupakan sebuah variabel dependen
Dan seperti
yang kita tahu, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen yang
disertainya.
Hal ini juga
berlaku untuk persepsi sederhana ini.
Lama
kelamaan persepsi ini akan berubah seiring dengan tekanan dari perubahan
fenomena yang ada. Dan tekanan itu adalah perubahan itu sendiri –mudeng ga?
Alah ya gimana ini nulisnya aku sendiri aja bingung-
Jadi, kita
ambil contoh saja.
Untuk Singapura
atau Jakarta misalnya, ceritanya jelas berbeda dengan Jogja. Masyarakat di
kedua kota ini sudah familier dengan vertical
building karena keterbatasan lahan yang sudah tidak dapat dibendung lagi.
Kenyataan ini lah yang memaksa mereka baik secara sadar atau tidak sadar
mengubah persepsi mereka terhadap tanah. Ya, bahwa tanah bukanlah kebutuhan
utama, melainkan ruang. Mereka tidak bisa merengek2 pada pemerintah untuk
diberikan tanah karena mereka sudah melihat sendiri kondisinya bahwa tidak ada
lagi tanah yang bisa dibangun. Kalaupun ada, jika hanya satu rumah atau satu
fungsi yang akan dibangun, jelas itu tidak masuk akal dan tidak efisien.
Disinilah
tepatnya aku bilang bahwa perubahan kenyataan menjadi variabel independen yang
siap menekan persepsi agar berubah, termodifikasi dan tersusun ulang.
Melalui
pergeseran persepsi, keterbatasan lahan bahkan tidak lagi perlu digolongkan
sebagai masalah, cukup sebagai fenomena. Begitu pula dengan model pembangunan vertical building yang kelak akan
tergolong sebagai bentuk adaptasi, bukan lagi sebuah opsi yang masuk kedalam
jajaran solusi.
Jadi
kesimpulannya?
Haha, entah
siapapun orang yang membuat mural itu, yang menulis ‘setiap orang butuh tanah’
-dan kuhitung sebagai representasi dari persepsi masyarakat- harus mulai mengubah
persepsinya, hal ini juga berlaku bagi semua orang yang tinggal di kota.
Masyarakat Jogja
harus mulai belajar membedakan dan menata ulang variabel di dalam strata
kebutuhan mereka.
Lambat laun,
disaat tidak ada lagi tanah yang terbentang bebas di kota ini maka mau tidak
mau mereka harus merevolusi persepsi mengenai posisi tanah dalam kehidupan
mereka.
Yang mereka
butuhkan bukanlah tanah, melainkan ruang.
To keep alive, they should start ‘climbing’, ‘losing
yard’, and re-translating what the elder ever said about things we must have:
“urep neng ndonya iku kudu duwe 3 perkoro, yaiku
sandang, pangan lan papan”
Iya, re-translating apakah papan itu adalah tanah, atau ruang sebagai tempat
tinggal.
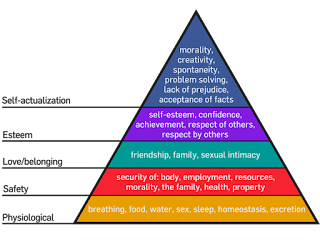

Wes go gae penelitian we koe tun, di dol jd jurnal. tak dukung.
BalasHapus